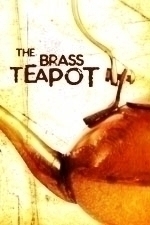Judul asli: The Monkey's Paw
Penulis: William W. Jacobs
Penulis: William W. Jacobs
Malam itu dingin dan lembab, namun api berkobar terang di perapian ruang keluarga mungil di Laburnum Villa, dimana Tuan White dan putranya, Herbert, sedang asyik bermain catur. Nyonya White, seorang wanita tua berambut putih, duduk merajut di depan perapian sambil sesekali melontarkan komentar tentang pertandingan catur tersebut.
"Coba dengar suara angin itu," tukas Tuan White. Dia telah keliru menggerakkan biji caturnya, dan dia ingin mengalihkan perhatian putranya agar tak melihatnya.
"Aku dengar, kok," tukas putranya, masih tetap berkonsentrasi pada papan caturnya.
"Kurasa dia tak akan datang malam ini," gumam sang ayah, menyentuh papan caturnya.
"Skak mat," ujar putranya sebagai jawaban.
"Itulah jeleknya tinggal di sini!" Tuan White mendadak menyentak. "Dari semua tempat terpencil lembab di luar sana, ini yang terburuk. Jalanannya seperti rawa-rawa dan sungai, tapi tak ada yang peduli karena memang hanya dua rumah di daerah ini yang ditinggali."
"Jangan khawatir, sayang," ujar Nyonya White. "Kau pasti akan menang lain kali."
Tuan White mengangkat kepalanya, tepat pada saat istri dan putranya bertukar pandang sekilas, dan dia buru-buru menyembunyikan seringai bersalah di balik janggut kelabunya.
"Itu dia," tukas Herbert ketika mendengar suara pintu pagar dan langkah kaki berat mendekati pintu.
Tuan White cepat-cepat berdiri untuk membuka pintu. Dia kembali bersama seorang pria tinggi kekar bermata kecil cemerlang dan berwajah kemerahan.
"Ini Sersan Mayor Morris," ujar Tuan White.
Prajurit itu menjabat tangan semua orang, lalu duduk dengan enak di depan perapian sementara Tuan White mengambil wiski dan beberapa buah gelas. Setelah minum tiga gelas, mata prajurit itu nampak semakin cerah, dan dia mulai mengoceh. Keluarga itu mendengarkan dengan tertarik saat sang prajurit yang telah berkelana jauh itu bercerita tentang berbagai petualangan seru, pengalamannya dalam perang, wabah, serta negeri-negeri asing.
"Dua puluh satu tahun yang lalu, ketika dia pergi, dia cuma bocah pekerja gudang," ujar Tuan White pada istri dan putranya. "Coba lihat dia sekarang."
"Dia memang nampak hebat," ujar Nyonya White, menyetujui dengan sopan.
"Aku ingin sekali bisa ke India," ujar Tuan White, "Kau tahu, cuma untuk melihat-lihat."
"Tidak, kau lebih baik kalau di sini saja," tukas si prajurit, menggelengkan kepalanya. Dia menaruh gelas kosongnya di meja, mendesah, lalu menggeleng lagi.
"Tapi aku ingin melihat kuil-kuil tua itu, melihat para fakir dan pemain akrobat," Tuan White melanjutkan. "Dan bagaimana dengan Cakar Monyet yang kau ceritakan padaku tempo hari, Morris?"
"Itu bukan apa-apa," tukas sang prajurit cepat. "Bukan cerita yang menarik."
"Cakar Monyet?" Tanya Nyonya White, tertarik.
"Yah...itu mungkin sesuatu yang akan kau sebut jimat." Ujar sang prajurit dengan santai. Keluarga itu mendengarkan dengan seksama, dan Tuan White mengisi gelasnya lagi.
"Kalau dilihat sepintas, itu hanya cakar monyet kering biasa," ujar Sersan Mayor Moris sambil mengeluarkan benda yang dimaksud dari sakunya. Nyonya White mundur sedikit dengan jijik, tapi putranya memeriksanya dengan seksama.
"Apa istimewanya benda ini?" Tanya Tuan White, mengambil benda itu dari tangan putranya, menelitinya, dan meletakkannya di meja.
"Seorang fakir tua memberi jampi-jampi ke benda ini. Dia orang suci yang ingin menunjukkan bahwa takdir menguasai kehidupan kita, dan mencoba mengubah takdir hanya akan membawa kesengsaraan. Jampi-jampinya membuat Cakar Monyet ini bisa mengabulkan tiga permintaan dari tiga orang yang berbeda."
Gayanya saat bercerita begitu mengesankan, membuat keluarga itu merasa bahwa letusan tawa mereka barusan kurang pantas.
"Nah, jadi apakah kau tak punya tiga permintaan?"
Sang prajurit menatapnya seolah dia anak bodoh. "Tentu saja aku punya," ujarnya pelan, dan raut wajahnya memucat.
"Dan apakah ketiga permintaanmu terkabul?" Tanya Nyonya White.
"Ya."
"Apakah ada yang sudah pernah memohon sebelumnya?" Nyonya itu terus mendesak.
"Yah, orang sebelum aku juga mendapat tiga permintaan. Aku tak tahu apa dua permintaan sebelumnya, tapi dia memohon untuk mati sebagai permintaan ketiganya. Itulah sebabnya aku mendapatkan cakar ini."
Dia nampak begitu serius sehingga keluarga itu terdiam.
"Kalau semua permintaanmu sudah terkabul, cakar itu tak ada gunanya lagi bagimu," ujar Tuan White. "Kenapa kau masih menyimpannya?"
Prajurit itu menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Oh, kayaknya aku cuma tertarik. Aku berpikir untuk menjualnya, tapi kurasa aku tak akan melakukannya. Cakar ini sudah menimbulkan cukup banyak masalah. Tapi toh tak ada yang mau membelinya. Mereka pikir ini cuma dongeng, dan yang percaya ingin mencobanya dulu sebelum membayar."
"Seandainya kau bisa punya tiga permintaan lagi," ujar Tuan White dengan nada tertarik, "Apakah kau akan meminta sesuatu?"
"Aku tak tahu, aku tak tahu!"
Sersan Mayor Morris mendadak menyambar Cakar Monyet itu dan melemparnya ke perapian. Tuan White memekik ngeri dan buru-buru membungkuk untuk mengambilnya.
"Biarkan saja itu terbakar," tukas sang prajurit.
"Kalau kau tak menginginkannya, Morris, berikan ini padaku."
"Tidak, aku sudah membuangnya! Kalau kau menyimpannya, jangan pernah salahkan aku. Berpikirlah yang lurus; lemparkan lagi benda itu ke api!"
Akan tetapi, Tuan White hanya mengamati benda itu dengan seksama, lantas menggelengkan kepalanya. "Bagaimana cara melakukannya, Morris?"
"Pegang dengan tangan kananmu, lalu ucapkan permintaannya keras-keras. Tapi kuingatkan padamu, akan ada konsekuensinya."
"Kedengaranya seperti di cerita Arabian Nights," ujar Nyonya White sambil mulai menyiapkan makan malam. "Hei, kenapa kau tidak minta empat pasang tangan ekstra untukku?"
Sang suami tertawa dan hendak mengucapkan permintaan, namun terdiam kaget ketika Sersan Mayor Morris menangkap lengannya.
"Kalau kau masih ngotot," ujarnya dengan nada tegas, "Mintalah sesuatu yang masuk akal."
Tuan White akhirnya menaruh kembali Cakar Monyet itu di sakunya, dan mereka semua duduk untuk makan malam. Jimat itu akhirnya terlupakan ketika sang prajurit mulai menyombong tentang petualangan serunya di India. Ketika dia akhirnya pamit, Tuan White berkomentar bahwa Cakar Monyet itu bisa jadi palsu, sama palsunya dengan cerita-cerita Morris.
"Apa kau membayarnya untuk benda itu?" Tanya Nyonya White.
"Oh, cuma sedikit. Dia menolak, tapi aku memaksanya. Dan dia menyuruhku lagi untuk membuang benda itu."
"Tentu saja!" Seru Herbert, sarkastis. "Kita semua bakal kaya dan terkenal! Coba ayah memohon untuk menjadi kaisar, jadi ibu tak akan bisa lagi menyuruh-nyuruh ayah."
Nyonya White pura-pura marah dan mengejar putranya melintasi meja makan, sementara Tuan White menatap Cakar Monyet itu dengan tatapan ragu.
"Jujur, aku tak tahu apa yang harus kuminta," ujarnya pelan. "Aku sudah punya semua yang kuinginkan."
"Kalau memohon agar pembayaran rumah kita selesai, ayah pasti mau, 'kan?" Tanya Herbert. "Mintalah dua ratus Pound. Sepertinya itu cukup."
Sang ayah, dengan berlagak malu, akhirnya mengacungkan jimat itu dengan tangan kanannya, sementara Herbert berkedip pada ibunya sebelum duduk di depan piano dan memainkan beberapa nada mencekam.
"Aku memohon uang dua ratus Pound," ujar Tuan White dengan tegas.
Ketika Herbert memainkan nada-nada dramatis, ayahnya mendadak menjerit dengan suara gemetar. Istri dan putranya segera berlari menghampirinya.
"Jimatnya bergerak!" Seru Tuan White sambil menatap ngeri ke jimat yang kini berada di lantai. "Saat aku mengucapkan permintaanku, cakar itu menggeliat di tanganku, seperti ular."
"Nah, aku tak melihat ada uang," ujar Herbert sambil memungut Cakar Monyet itu. "Dan kurasa tak akan pernah ada uang."
"Itu pasti hanya bayanganmu," ujar Nyonya White, menatap suaminya dengan cemas.
Suaminya menggeleng. "Tak apa-apa. Tak ada yang terluka. Aku kaget, itu saja."
Mereka duduk lagi di depan perapian. Saat Tuan White mengisap pipa rokoknya, angin bertiup makin kencang di luar, dan dia menjadi gugup ketika mendengar suara pintu terbanting menutup di lantai dua. Keheningan yang ganjil dan mencekam melanda keluarga itu. Pasangan itu akhirnya memutuskan untuk tidur.
"Mungkin nanti ada kantong uang besar muncul di tempat tidurmu," ujar Herbert bercanda sebelum mengucapkan selamat malam pada mereka.
Herbert duduk selama beberapa waktu di kegelapan, memandang perapian, dan melihat bayangan wajah-wajah di kobaran api. Salah satu wajah itu nampak mengerikan, seperti monyet, dan dia hanya bisa terpana menatapnya. Ketika dia menyadari bahwa Cakar Monyet itu masih ada di genggamannya, dia cepat-cepat melemparnya dengan gemetar sebelum menyapukan tangannya pada bajunya, sebelum pergi tidur.
"Kalau dilihat sepintas, itu hanya cakar monyet kering biasa," ujar Sersan Mayor Moris sambil mengeluarkan benda yang dimaksud dari sakunya. Nyonya White mundur sedikit dengan jijik, tapi putranya memeriksanya dengan seksama.
"Apa istimewanya benda ini?" Tanya Tuan White, mengambil benda itu dari tangan putranya, menelitinya, dan meletakkannya di meja.
"Seorang fakir tua memberi jampi-jampi ke benda ini. Dia orang suci yang ingin menunjukkan bahwa takdir menguasai kehidupan kita, dan mencoba mengubah takdir hanya akan membawa kesengsaraan. Jampi-jampinya membuat Cakar Monyet ini bisa mengabulkan tiga permintaan dari tiga orang yang berbeda."
Gayanya saat bercerita begitu mengesankan, membuat keluarga itu merasa bahwa letusan tawa mereka barusan kurang pantas.
"Nah, jadi apakah kau tak punya tiga permintaan?"
Sang prajurit menatapnya seolah dia anak bodoh. "Tentu saja aku punya," ujarnya pelan, dan raut wajahnya memucat.
"Dan apakah ketiga permintaanmu terkabul?" Tanya Nyonya White.
"Ya."
"Apakah ada yang sudah pernah memohon sebelumnya?" Nyonya itu terus mendesak.
"Yah, orang sebelum aku juga mendapat tiga permintaan. Aku tak tahu apa dua permintaan sebelumnya, tapi dia memohon untuk mati sebagai permintaan ketiganya. Itulah sebabnya aku mendapatkan cakar ini."
Dia nampak begitu serius sehingga keluarga itu terdiam.
"Kalau semua permintaanmu sudah terkabul, cakar itu tak ada gunanya lagi bagimu," ujar Tuan White. "Kenapa kau masih menyimpannya?"
Prajurit itu menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Oh, kayaknya aku cuma tertarik. Aku berpikir untuk menjualnya, tapi kurasa aku tak akan melakukannya. Cakar ini sudah menimbulkan cukup banyak masalah. Tapi toh tak ada yang mau membelinya. Mereka pikir ini cuma dongeng, dan yang percaya ingin mencobanya dulu sebelum membayar."
"Seandainya kau bisa punya tiga permintaan lagi," ujar Tuan White dengan nada tertarik, "Apakah kau akan meminta sesuatu?"
"Aku tak tahu, aku tak tahu!"
Sersan Mayor Morris mendadak menyambar Cakar Monyet itu dan melemparnya ke perapian. Tuan White memekik ngeri dan buru-buru membungkuk untuk mengambilnya.
"Biarkan saja itu terbakar," tukas sang prajurit.
"Kalau kau tak menginginkannya, Morris, berikan ini padaku."
"Tidak, aku sudah membuangnya! Kalau kau menyimpannya, jangan pernah salahkan aku. Berpikirlah yang lurus; lemparkan lagi benda itu ke api!"
Akan tetapi, Tuan White hanya mengamati benda itu dengan seksama, lantas menggelengkan kepalanya. "Bagaimana cara melakukannya, Morris?"
"Pegang dengan tangan kananmu, lalu ucapkan permintaannya keras-keras. Tapi kuingatkan padamu, akan ada konsekuensinya."
"Kedengaranya seperti di cerita Arabian Nights," ujar Nyonya White sambil mulai menyiapkan makan malam. "Hei, kenapa kau tidak minta empat pasang tangan ekstra untukku?"
Sang suami tertawa dan hendak mengucapkan permintaan, namun terdiam kaget ketika Sersan Mayor Morris menangkap lengannya.
"Kalau kau masih ngotot," ujarnya dengan nada tegas, "Mintalah sesuatu yang masuk akal."
Tuan White akhirnya menaruh kembali Cakar Monyet itu di sakunya, dan mereka semua duduk untuk makan malam. Jimat itu akhirnya terlupakan ketika sang prajurit mulai menyombong tentang petualangan serunya di India. Ketika dia akhirnya pamit, Tuan White berkomentar bahwa Cakar Monyet itu bisa jadi palsu, sama palsunya dengan cerita-cerita Morris.
"Apa kau membayarnya untuk benda itu?" Tanya Nyonya White.
"Oh, cuma sedikit. Dia menolak, tapi aku memaksanya. Dan dia menyuruhku lagi untuk membuang benda itu."
"Tentu saja!" Seru Herbert, sarkastis. "Kita semua bakal kaya dan terkenal! Coba ayah memohon untuk menjadi kaisar, jadi ibu tak akan bisa lagi menyuruh-nyuruh ayah."
Nyonya White pura-pura marah dan mengejar putranya melintasi meja makan, sementara Tuan White menatap Cakar Monyet itu dengan tatapan ragu.
"Jujur, aku tak tahu apa yang harus kuminta," ujarnya pelan. "Aku sudah punya semua yang kuinginkan."
"Kalau memohon agar pembayaran rumah kita selesai, ayah pasti mau, 'kan?" Tanya Herbert. "Mintalah dua ratus Pound. Sepertinya itu cukup."
Sang ayah, dengan berlagak malu, akhirnya mengacungkan jimat itu dengan tangan kanannya, sementara Herbert berkedip pada ibunya sebelum duduk di depan piano dan memainkan beberapa nada mencekam.
"Aku memohon uang dua ratus Pound," ujar Tuan White dengan tegas.
Ketika Herbert memainkan nada-nada dramatis, ayahnya mendadak menjerit dengan suara gemetar. Istri dan putranya segera berlari menghampirinya.
"Jimatnya bergerak!" Seru Tuan White sambil menatap ngeri ke jimat yang kini berada di lantai. "Saat aku mengucapkan permintaanku, cakar itu menggeliat di tanganku, seperti ular."
"Nah, aku tak melihat ada uang," ujar Herbert sambil memungut Cakar Monyet itu. "Dan kurasa tak akan pernah ada uang."
"Itu pasti hanya bayanganmu," ujar Nyonya White, menatap suaminya dengan cemas.
Suaminya menggeleng. "Tak apa-apa. Tak ada yang terluka. Aku kaget, itu saja."
Mereka duduk lagi di depan perapian. Saat Tuan White mengisap pipa rokoknya, angin bertiup makin kencang di luar, dan dia menjadi gugup ketika mendengar suara pintu terbanting menutup di lantai dua. Keheningan yang ganjil dan mencekam melanda keluarga itu. Pasangan itu akhirnya memutuskan untuk tidur.
"Mungkin nanti ada kantong uang besar muncul di tempat tidurmu," ujar Herbert bercanda sebelum mengucapkan selamat malam pada mereka.
Herbert duduk selama beberapa waktu di kegelapan, memandang perapian, dan melihat bayangan wajah-wajah di kobaran api. Salah satu wajah itu nampak mengerikan, seperti monyet, dan dia hanya bisa terpana menatapnya. Ketika dia menyadari bahwa Cakar Monyet itu masih ada di genggamannya, dia cepat-cepat melemparnya dengan gemetar sebelum menyapukan tangannya pada bajunya, sebelum pergi tidur.
***
Keesokan harinya, Herbert tertawa mengingat ketakutannya malam sebelumnya. Matahari musim dingin menyinari ruangan yang kini nampak normal-normal saja, dan Cakar Monyet kering yang kotor itu masih ada di lantai setelah dia melemparkannya.
"Semua prajurit tua sama saja, kukira," ujar Nyonya White. "Buat apa kita mendengarkan omong kosong seperti itu? Bagaimana mungkin permintaan dikabulkan begitu saja? Kalaupun bisa, bagaimana mungkin uang dua ratus Pound akan menyakiti kita?"
"Bisa saja uang itu jatuh dari langit menimpa kepala ayah," canda Herbert.
"Morris bilang, permintaan kita terjadi secara alami," ujar ayahnya. "Mungkin terjadi karena kebetulan."
"Kalau begitu, jangan habiskan uangnya sebelum aku pulang," ujar Herbert, lalu pergi ke luar. Ibunya memerhatikannya saat dia menyusuri jalan desa ke tempat kerjanya. Tentu saja dia tak percaya jimat itu benar-benar bisa mengabulkan permintaan, tetapi Nyonya White tetap berlari menuju pintu saat tukang pos mengetuknya, dan merasa kecewa ketika tahu tukang pos hanya membawa surat tagihan.
"Herbert pasti akan meledek kita soal ini nanti," ujar Nyonya White.
"Ya, pasti," ujar Tuan White. "Tapi benda itu benar-benar bergerak di tanganku, aku yakin sekali."
"Maksudmu, kau pikir benda itu bergerak."
"Tidak, benda itu benar-benar bergerak, kuberitahu kau. Aku tidak...ada apa?"
Nyonya White tidak menjawab. Wanita itu memerhatikan seseorang di luar, yang sepertinya sedang mengira-ngira apakah dia sebaiknya membuka pintu pagar atau tidak. Orang itu berpakaian bagus dan mengenakan topi sutra, dan dia berhenti tiga kali di depan pintu pagar sebelum berjalan menjauh. Akhirnya, ketika datang untuk yang keempat kalinya, dia menaruh tangannya di pintu pagar, membukanya, dan masuk. Nyonya White membuka pintu dan menyilakan orang itu masuk. Tamu itu nampak khawator dan tak nyaman, dan hanya berani menatap mereka dari sudut matanya.
"Saya...saya diminta datang," ujarnya ragu-ragu. "Saya dari Maw and Meggins."
Nyonya White nampak terperanjat. "Ada apa? Apakah ada yang terjadi pada Herbert?"
"Nah, nah, jangan cemas begitu," tukas suaminya. "Aku yakin bukan berita buruk. Bukankah begitu, tuan?" Dia menatap tamunya dengan penuh harap.
"Maafkan saya...."
"Apakah dia terluka?" Tuntut Nyonya White.
Sang tamu menunduk. "Parah sekali," ujarnya pelan. "Tapi dia tidak kesakitan."
"Oh, syukurlah!"
Akan tetapi, makna mengerikan dari perkataan tamunya barusan pelan-pelan meresap, dan Nyonya White akhirnya menatapnya. Sang tamu memalingkan wajahnya, memastikan ketakutan terbesarnya. Sang nyonya menahan napas dan meletakkan tangannya yang gemetar di atas tangan suaminya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu.
"Dia terperangkap di dalam mesin," ujar sang tamu pelan.
"Terperangkap?" Gumam Tuan White, masih nampak bingung. Dia menatap pintu dan menggenggam tangan istrinya erat-erat, seperti ketika mereka masih pasangan muda, empat puluh tahun yang lalu. "Dia anak tunggal," ujarnya pada tamunya. "Ini berat sekali."
Sang tamu batuk pelan, dan berdiri lalu berjalan ke jendela. "Perusahaan meminta saya menyampaikan rasa simpati mereka atas tragedi ini," ujarnya tanpa berani melihat ke pasangan tua itu.
Tak ada jawaban. Nyonya White nampak pucat, matanya menatap ke kejauhan. Ekspresi wajah Tuan White nampak gelap dan serius.
"Saya juga harus memberitahu bahwa Maw and Meggins tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut," ujar sang tamu lagi. "Tapi, sebagai penghargaan atas kerja putra Anda selama ini, mereka memberikan Anda kompensasi."
Tuan White melepaskan tangan istrinya dan menatap sang tamu dengan ngeri.
"Berapa?"
"Dua ratus Pound."
Tuan White tersenyum samar, mengulurkan tangan selaku orang buta, sebelum ambruk ke lantai dan pingsan.
"Saya...saya diminta datang," ujarnya ragu-ragu. "Saya dari Maw and Meggins."
Nyonya White nampak terperanjat. "Ada apa? Apakah ada yang terjadi pada Herbert?"
"Nah, nah, jangan cemas begitu," tukas suaminya. "Aku yakin bukan berita buruk. Bukankah begitu, tuan?" Dia menatap tamunya dengan penuh harap.
"Maafkan saya...."
"Apakah dia terluka?" Tuntut Nyonya White.
Sang tamu menunduk. "Parah sekali," ujarnya pelan. "Tapi dia tidak kesakitan."
"Oh, syukurlah!"
Akan tetapi, makna mengerikan dari perkataan tamunya barusan pelan-pelan meresap, dan Nyonya White akhirnya menatapnya. Sang tamu memalingkan wajahnya, memastikan ketakutan terbesarnya. Sang nyonya menahan napas dan meletakkan tangannya yang gemetar di atas tangan suaminya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan itu.
"Dia terperangkap di dalam mesin," ujar sang tamu pelan.
"Terperangkap?" Gumam Tuan White, masih nampak bingung. Dia menatap pintu dan menggenggam tangan istrinya erat-erat, seperti ketika mereka masih pasangan muda, empat puluh tahun yang lalu. "Dia anak tunggal," ujarnya pada tamunya. "Ini berat sekali."
Sang tamu batuk pelan, dan berdiri lalu berjalan ke jendela. "Perusahaan meminta saya menyampaikan rasa simpati mereka atas tragedi ini," ujarnya tanpa berani melihat ke pasangan tua itu.
Tak ada jawaban. Nyonya White nampak pucat, matanya menatap ke kejauhan. Ekspresi wajah Tuan White nampak gelap dan serius.
"Saya juga harus memberitahu bahwa Maw and Meggins tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut," ujar sang tamu lagi. "Tapi, sebagai penghargaan atas kerja putra Anda selama ini, mereka memberikan Anda kompensasi."
Tuan White melepaskan tangan istrinya dan menatap sang tamu dengan ngeri.
"Berapa?"
"Dua ratus Pound."
Tuan White tersenyum samar, mengulurkan tangan selaku orang buta, sebelum ambruk ke lantai dan pingsan.
***
Setelah memakamkan putra mereka secara besar-besaran di pemakaman dua mil jauhnya, pasangan tua itu kembali ke rumah mereka yang muram dan hening. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka nyaris tidak menyadarinya. Mereka mengharapkan sesuatu yang lain akan terjadi, untuk menghilangkan beban berat dari hati mereka yang tua. Akan tetapi, hari demi hari berlalu, dan harapan mereka berganti dengan keputusasaan. Mereka jarang bicara, karena sudah tak banyak yang bisa dibicarakan. Setiap hari terasa panjang dan sepi.
Sekitar seminggu kemudian, sang suami terbangun di tengah malam karena mendengar suara tangisan dekat jendela kamarnya. Dia duduk beberapa saat, mendengarkan.
"Ayolah," ujarnya lembut. "Kembalilah tidur, kau akan kedinginan."
"Di luar lebih dingin lagi untuk anakku," ujar istrinya sambil terus menangis.
Suara tangisan pelan-pelan mereda ketika sang suami memutuskan tidur lagi, namun seruan keras istrinya membuatnya terperanjat bangun.
"Cakarnya!" Seru sang istri. "Cakar monyet itu!"
"Kenapa? Di mana? Ada apa?" Suaminya berseru panik.
Sang istri mendekatinya. "Aku memerlukannya. Apakah kau menghancurkannya?"
"Ada di ruang tamu," ujar suaminya heran. "Kenapa?"
"Aku baru memikirkannya," ujar sang istri, nyaris histeris. "Kenapa aku tak memikirkannya sebelumnya? Kenapa kau tak memikirkannya?"
"Memikirkan apa?"
"Dua permintaan kita yang lain. Kita baru meminta satu."
"Apakah yang satu itu tidak cukup!?" Raung sang suami.
"Tidak, tidak, kita hanya akan gunakan satu lagi. Turunlah dan mintalah agar anak kita hidup lagi."
Sang suami terduduk di tempat tidur dan menyibakkan selimut dengan gemetar.
"Demi Tuhan, kau gila!"
"Ambillah," ujar istrinya dengan napas tersengal. "Ambil, cepat, dan mintalah. Anakku, oh, anakku!"
Tuan White menyalakan lilin. "Pergilah tidur. Kau tak tahu apa yang kau katakan."
Tapi istrinya terus meracau. "Permintaan pertama kita dikabulkan. Kenapa tidak yang kedua?"
"Itu cuma kebetulan," gagap suaminya.
"Ambil. Mintalah," ujar istrinya dengan gemetar karena bersemangat.
Suaminya menatapnya, lantas berkata dengan suara gemetar, "Dia sudah mati sepuluh hari, dan aku pun hanya bisa mengenalinya dari pakaiannya. Mayatnya terlalu mengerikan untuk kau lihat. Kau pikir sudah jadi seperti apa dia sekarang?"
Tapi, istrinya menariknya menuju pintu. "Hidupkan lagi dia. Kau pikir aku takut pada anakku sendiri?"
Sang suami menuruni tangga, meraba-raba dalam kegelapan sampai dia merasakan tempat gantungan mantel. Jimat itu ada di sana.
Mendadak, dia merasa takut kalau-kalau permintaannya yang tak terucap akan terkabul, dan mayat anaknya yang terkoyak-koyak akan kembali sebelum dia sempat melarikan diri dari ruangan itu. Sambil berkeringat dingin, dia terus meraba-raba melewati meja dan dinding, sampai akhirnya dia tiba di lorong menuju kamar. Jimat kering yang kotor berkerut-kerut itu tergenggam di tangannya.
Wajah istrinya nampak berbeda saat dia memasuki kamar; pucat dan penuh harap, dan ekspresinya yang ganjil membuat suaminya ketakutan.
"Mintalah!" Seru istrinya.
"Ini bodoh," ujar suaminya, ragu-ragu.
"Mintalah!" Ulang sang istri.
Sang suami akhirnya mengangkat tangannya. "Aku memohon agar anakku hidup lagi."
Cakar Monyet itu jatuh ke lantai. Sang suami menatapnya dengan ketakutan, lantas dia terduduk dengan gemetar di kursi. Sang istri, dengan mata menyala-nyala, berjalan ke jendela dan menarik tirainya terbuka. Tuan White tetap duduk, merinding sampai ke tulang, sesekali melirik ke arah istrinya yang sedang memandang ke luar jendela. Api lilin yang sudah semakin pendek memantulkan bayang-bayang yang bergoyang-goyang di langit-langit dan dinding, sebelum akhirnya padam. Sang suami merasa sangat lega ketika menyadari permintaannya tidak terkabul, dan merayap kembali ke tempat tidur. Beberapa menit kemudian, istrinya menyusul dalam keheningan dan depresi.
Keduanya tak berbicara, melainkan mendengar suara tik-tok jam dinding. Tangga berkeriut; seekor tikus terdengar berlari di balik dinding. Kegelapan itu terasa menekan. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Tuan White akhirnya menyalakan sebatang korek api, membawa kotak korek, dan berjalan menuruni tangga.
Api korek padam ketika Tuan White tiba di dasar tangga. Tuan White berhenti untuk menyalakan sebatang korek, dan di saat yang bersamaan, terdengar suara ketukan di pintu, ketukan yang begitu pelan sehingga nyaris tak terdengar.
Korek api terjatuh dari tangan Tuan White ketika dia berdiri terpaku seperti patung, napasnya tercekat. Suara ketukan itu lagi. Tuan White berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu. Suara ketukan itu terdengar lagi di bawah.
"Apa itu?" Seru istrinya, terduduk.
"Tikus," ujar Tuan White gemetar. "Ada tikus berlari melewatiku di tangga."
Istrinya duduk mendengarkan. Suara ketukan kembali bergema ke seluruh rumah.
"Herbert!" Seru sang istri. "Itu Herbert!"
Sang istri berlari ke pintu kamar, namun suaminya lebih cepat. Dia menyambar istrinya dan merangkulnya erat.
"Apa yang akan kau lakukan?" Desisnya.
Nyonya White berusaha melepaskan dirinya. "Itu anakku. Itu Herbert! Aku sudah lupa dia dimakamkan dua mil jauhnya. Kenapa kau memegangiku? Lepaskan aku, aku harus membuka pintu!"
"Demi Tuhan, jangan biarkan dia masuk!" Jerit suaminya.
"Kau takut pada anakmu sendiri? Lepaskan aku! Ibu datang, Herbert, ibu datang!"
Suara ketukan itu terdengar lagi, dan lagi. Dengan satu sentakan, sang istri membebaskan dirinya, dan berlari keluar kamar. Tuan White mengikutinya ke tangga dan berteriak-teriak memohon saat istrinya berlari menuruni tangga. Dia mendengar rantai pintu dilepas, dan gerendel pintu bagian bawah terbuka. Suara Nyonya White terdengar tersengal, "Gerendel atasnya! Aku tak bisa mencapainya! Turunlah!"
Akan tetapi, Tuan White sedang merangkak di lantai dan meraba-raba, berusaha mencari Cakar Monyet itu. Kalau saja dia bisa menemukannya sebelum makhluk itu masuk! Suara ketukan susul-menyusul bergema ke seluruh rumah. Dia bisa mendengar suara kursi bergeser di lantai saat istrinya menariknya. Dia mendengar suara gerendel dibuka, dan pada saat yang bersamaan, dia menemukan Cakar Monyet itu dan bergegas mengucapkan permintaan ketiganya.
Suara ketukan mendadak berhenti, tetapi gemanya masih terngiang. Dia mendengar suara kursi digeser kembali, dan daun pintu dibuka. Hembusan angin dingin bertiup ke arah tangga, membawa ratapan sedih dan kecewa istrinya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk berlari ke sisi istrinya, lantas ke pintu pagar. Lampu di seberang rumahnya berkedip-kedip menyinari jalanan yang sepi.
Tamat