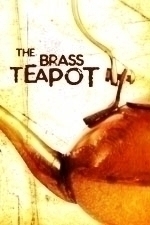Judul asli: The Brass Teapot
Penulis: Tim Macy
Penulis: Tim Macy
Wanita tua penjaga kios barang antik di tepi jalan itu berbicara dengan logat Eropa Timur yang kental. Ia berjalan mengitari meja pajangan dengan sepasang kaki pincang yang terbungkus celana kulit longgar, namun tanpa sepatu. John tak bisa tidak memandang jari-jari kaki wanita itu, yang menghitam seolah pernah membeku parah. Sebenarnya, keseluruhan penampilannya nampak seolah ia pernah sangat kedinginan dan tak pernah kembali normal.
Alice dan John baru saja pulang dari mengunjungi putri sulung mereka di kampusnya. Mereka hanya berhenti agar John bisa meluruskan punggungnya yang nyeri. Alice tidur sepanjang perjalanan, atau setidaknya pura-pura tidur, karena ia memikirkan sejumlah besar uang yang telah mereka keluarkan untuk biaya pendidikan putri mereka. Keduanya telah membatalkan rencana berlibur karena sang putri harus mengulang kelas aljabar di musim panas.
Wanita tua itu kini menghampiri Alice. Jemarinya yang panjang menyorongkan sebuah teko kuningan ke tangan Alice. Kulitnya yang nyaris transparan nampak ikut bergelayut seiring gerakan itu.
"Terima kasih," ujar Alice sopan, bingung harus mengatakan apa.
Dilihatnya stan barang antik milik wanita itu, yang terdiri dari sebuah meja hijau, yang permukaannya dipenuhi berbagai benda usang dari masa lalu. Kenang-kenangan serba logam yang berat.
John memutar bola matanya ketika istrinya meletakkan teko kuningan itu di kursi belakang Ford Festiva mereka. Mobil itu nampak harus berjuang keras ketika menyusuri jalan raya antar negara bagian, keberatan oleh beban koper-koper perjalanan akhir pekan.
Sepanjang perjalanan pulang, keduanya bertengkar tentang uang yang terbuang-buang. Kedua anak mereka kuliah, dan karena keduanya tak mampu mempertahankan beasiswa mereka, tabungan pensiun John dan Alice jadi menyusut, dan mereka tak tahu lagi bagaimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang bahkan ada hipotek kedua yang harus dibayar.
Setelah mobil tersebut masuk ke pekarangan, keduanya langsung turun dan mengambil koper masing-masing. John tanpa sengaja menghantam jari Alice dengan pintu bagasi mobil, sebelum istrinya itu sempat menarik tangannya.
"Maafkan aku...." kata John, meraih tangan istrinya dan menciumnya. Terdengar suara berkelontang dari dalam mobil, seolah ada yang mengetuk teko kuningan itu. Ketika jari Alice sudah berhenti berdenyut, ia meraih teko itu dan mengangkat tutupnya. Ada uang lima sen di dalamnya.
"Nah, sekarang sudah lunas," tukas Alice.
Tetap saja, John merasa kesal melihat teko kuningan itu.
Selama empat hari berikutnya, ia terus merasa terganggu dengan kehadiran teko yang nampak kuno itu di dapur modern mereka. Keduanya telah mengganti semua bagian dapur ketika anak-anak mereka pindah. Mereka telah membeli kulkas dua pintu dan oven dengan permukaan mengilap yang bisa membersihkan sendiri. Kalau saja mereka tahu anak-anak mereka tak akan bisa mempertahankan beasiswa mereka, mereka pasti tak akan melakukannya. Dalam tiga tahun, semuanya sudah harus dilunasi, dan garansinya akan habis.
John semakin kesal ketika istrinya memutuskan membuat kopi dengan teko itu.
"Poci elektriknya rusak," ujar Alice beralasan.
John memandangi istrinya, berdiri di dapur dengan pakaian kantor dan rambut kelabu yang diikat kuncir kuda, dengan kikuk merebus air dan menambahkan bubuk kopi.
"Aku belum pernah membuatnya dengan cara ini," ujar Alice, mengaduk cairan di dalam teko dengan sendok plastik, yang tentu saja langsung meleleh. John ingin menunjukkan cara yang benar, namun rasanya terlalu cepat untuk mulai memerintah-merintah istrinya. Lagipula, mood mereka baru meningkat setelah minum kopi dan sarapan. Semua ciuman, pelukan dan ekspresi kasih baru muncul setelah kafein merasuk.
"Kamu harusnya mengaduknya seperti ini...." ujar John, memasukkan sendok logam ke dalam teko yang menghitam. Alice melengos ke arah lain, seperti biasa kalau John mengkritiknya.
"Jangan!" Seru Alice mendadak. Ia mendorong John ke samping, menyebabkan teko terguling dan menumpahkan cairan panas mendidih ke pergelangan tangan suaminya. John memekik, lantas duduk di kursi dapur dan memegangi kulitnya yang berubah merah muda hingga istrinya datang membawa kantung es.
"Nanti melepuh," ujar Alice, menempelkan kantung es itu ke kulit John. John hanya mengangguk, dan keduanya tak bicara apa-apa lagi hingga Alice menuangkan kopi dan dirinya membuat roti panggang untuk mereka berdua.
"Jam berapa kau akan pulang nanti malam?" Tanya Alice.
"Aku mungkin akan terlambat," jawab John. Ada kiriman-kiriman besar berdatangan dari seluruh penjuru negeri, dan hanya John sendiri yang bisa mengoperasikan sistem pemrosesan baru untuk pemesanan dalam jumlah besar. Sebenarnya ada satu orang lagi yang bisa melakukannya; seorang karyawan wanita yang baru saja lulus kuliah. Akan tetapi, John menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan ini, karena jika karyawan baru itu dipandang terlalu mumpuni, John mungkin akan dipecat.
Ketika John sudah berdiri untuk mencium sang istri setelah tegukan kopi terakhirnya, ia merasakan sesuatu di dalam mulutnya.
"Apa kau sudah mencuci teko ini?" Tanyanya.
"Tentu saja, sudah bersih."
John kemudian menarik gumpalan kertas yang menempel di langit-langit mulutnya. Selembar uang dua dolar.
"Kalau begitu, ini apa?"
Keduanya kemudian berdiri separuh membungkuk di atas meja dapur, dimana John membentangkan uang itu untuk mengeringkannya. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa uang itu bisa ada di sana, walaupun Alice bersikeras ia sudah menggosok setiap permukaan luar dan dalam teko itu.
Alice dan John kemudian berciuman, masing-masing menyesali pertengkaran yang sudah terjadi sepanjang akhir pekan. Lidah Alice menyelinap ke sela-sela gigi-geligi John, membuatnya menggeliat. Ketika John meraih ke kemeja katun istrinya untuk membukanya, pergelangan tangannya yang tersiram air panas tergesek, dan ia memekik kesakitan.
Sekeping uang logam jatuh ke dalam teko.
Alice dan John memandangi teko itu dengan takjub. John memungut uang itu dari dalam teko, mengangkat dan melihatnya di bawah cahaya. Alice mendadak mengulurkan tangan dan mencubit lengan suaminya sekuat tenaga. Sebelum John sempat menyingkirkan tangan istrinya, beberapa keping uang logam kembali jatuh ke dalam teko.
"Kenapa bisa begitu?" Gumam John.
"Pukul aku," ujar Alice.
John menatap istrinya.
"Tidak usah pukul aku sampai pingsan. Pukul saja aku di lengan sampai memar."
John tidak mau memukul istrinya. Alih-alih, ia menyambar tasnya dan berjalan ke pintu depan.
"Kalau aku terlambat, karyawan baru itu akan mengambil alih pekerjaan pengiriman. Aku harus mendapat semua uang lembur. Kita harus membayar uang kuliah anak-anak."
Ia mencium Alice, lalu keluar dan menutup pintu.
Wanita tua itu kini menghampiri Alice. Jemarinya yang panjang menyorongkan sebuah teko kuningan ke tangan Alice. Kulitnya yang nyaris transparan nampak ikut bergelayut seiring gerakan itu.
"Terima kasih," ujar Alice sopan, bingung harus mengatakan apa.
Dilihatnya stan barang antik milik wanita itu, yang terdiri dari sebuah meja hijau, yang permukaannya dipenuhi berbagai benda usang dari masa lalu. Kenang-kenangan serba logam yang berat.
John memutar bola matanya ketika istrinya meletakkan teko kuningan itu di kursi belakang Ford Festiva mereka. Mobil itu nampak harus berjuang keras ketika menyusuri jalan raya antar negara bagian, keberatan oleh beban koper-koper perjalanan akhir pekan.
Sepanjang perjalanan pulang, keduanya bertengkar tentang uang yang terbuang-buang. Kedua anak mereka kuliah, dan karena keduanya tak mampu mempertahankan beasiswa mereka, tabungan pensiun John dan Alice jadi menyusut, dan mereka tak tahu lagi bagaimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekarang bahkan ada hipotek kedua yang harus dibayar.
Setelah mobil tersebut masuk ke pekarangan, keduanya langsung turun dan mengambil koper masing-masing. John tanpa sengaja menghantam jari Alice dengan pintu bagasi mobil, sebelum istrinya itu sempat menarik tangannya.
"Maafkan aku...." kata John, meraih tangan istrinya dan menciumnya. Terdengar suara berkelontang dari dalam mobil, seolah ada yang mengetuk teko kuningan itu. Ketika jari Alice sudah berhenti berdenyut, ia meraih teko itu dan mengangkat tutupnya. Ada uang lima sen di dalamnya.
"Nah, sekarang sudah lunas," tukas Alice.
Tetap saja, John merasa kesal melihat teko kuningan itu.
***
Selama empat hari berikutnya, ia terus merasa terganggu dengan kehadiran teko yang nampak kuno itu di dapur modern mereka. Keduanya telah mengganti semua bagian dapur ketika anak-anak mereka pindah. Mereka telah membeli kulkas dua pintu dan oven dengan permukaan mengilap yang bisa membersihkan sendiri. Kalau saja mereka tahu anak-anak mereka tak akan bisa mempertahankan beasiswa mereka, mereka pasti tak akan melakukannya. Dalam tiga tahun, semuanya sudah harus dilunasi, dan garansinya akan habis.
John semakin kesal ketika istrinya memutuskan membuat kopi dengan teko itu.
"Poci elektriknya rusak," ujar Alice beralasan.
John memandangi istrinya, berdiri di dapur dengan pakaian kantor dan rambut kelabu yang diikat kuncir kuda, dengan kikuk merebus air dan menambahkan bubuk kopi.
"Aku belum pernah membuatnya dengan cara ini," ujar Alice, mengaduk cairan di dalam teko dengan sendok plastik, yang tentu saja langsung meleleh. John ingin menunjukkan cara yang benar, namun rasanya terlalu cepat untuk mulai memerintah-merintah istrinya. Lagipula, mood mereka baru meningkat setelah minum kopi dan sarapan. Semua ciuman, pelukan dan ekspresi kasih baru muncul setelah kafein merasuk.
"Kamu harusnya mengaduknya seperti ini...." ujar John, memasukkan sendok logam ke dalam teko yang menghitam. Alice melengos ke arah lain, seperti biasa kalau John mengkritiknya.
"Jangan!" Seru Alice mendadak. Ia mendorong John ke samping, menyebabkan teko terguling dan menumpahkan cairan panas mendidih ke pergelangan tangan suaminya. John memekik, lantas duduk di kursi dapur dan memegangi kulitnya yang berubah merah muda hingga istrinya datang membawa kantung es.
"Nanti melepuh," ujar Alice, menempelkan kantung es itu ke kulit John. John hanya mengangguk, dan keduanya tak bicara apa-apa lagi hingga Alice menuangkan kopi dan dirinya membuat roti panggang untuk mereka berdua.
"Jam berapa kau akan pulang nanti malam?" Tanya Alice.
"Aku mungkin akan terlambat," jawab John. Ada kiriman-kiriman besar berdatangan dari seluruh penjuru negeri, dan hanya John sendiri yang bisa mengoperasikan sistem pemrosesan baru untuk pemesanan dalam jumlah besar. Sebenarnya ada satu orang lagi yang bisa melakukannya; seorang karyawan wanita yang baru saja lulus kuliah. Akan tetapi, John menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan ini, karena jika karyawan baru itu dipandang terlalu mumpuni, John mungkin akan dipecat.
Ketika John sudah berdiri untuk mencium sang istri setelah tegukan kopi terakhirnya, ia merasakan sesuatu di dalam mulutnya.
"Apa kau sudah mencuci teko ini?" Tanyanya.
"Tentu saja, sudah bersih."
John kemudian menarik gumpalan kertas yang menempel di langit-langit mulutnya. Selembar uang dua dolar.
"Kalau begitu, ini apa?"
Keduanya kemudian berdiri separuh membungkuk di atas meja dapur, dimana John membentangkan uang itu untuk mengeringkannya. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa uang itu bisa ada di sana, walaupun Alice bersikeras ia sudah menggosok setiap permukaan luar dan dalam teko itu.
Alice dan John kemudian berciuman, masing-masing menyesali pertengkaran yang sudah terjadi sepanjang akhir pekan. Lidah Alice menyelinap ke sela-sela gigi-geligi John, membuatnya menggeliat. Ketika John meraih ke kemeja katun istrinya untuk membukanya, pergelangan tangannya yang tersiram air panas tergesek, dan ia memekik kesakitan.
Sekeping uang logam jatuh ke dalam teko.
Alice dan John memandangi teko itu dengan takjub. John memungut uang itu dari dalam teko, mengangkat dan melihatnya di bawah cahaya. Alice mendadak mengulurkan tangan dan mencubit lengan suaminya sekuat tenaga. Sebelum John sempat menyingkirkan tangan istrinya, beberapa keping uang logam kembali jatuh ke dalam teko.
"Kenapa bisa begitu?" Gumam John.
"Pukul aku," ujar Alice.
John menatap istrinya.
"Tidak usah pukul aku sampai pingsan. Pukul saja aku di lengan sampai memar."
John tidak mau memukul istrinya. Alih-alih, ia menyambar tasnya dan berjalan ke pintu depan.
"Kalau aku terlambat, karyawan baru itu akan mengambil alih pekerjaan pengiriman. Aku harus mendapat semua uang lembur. Kita harus membayar uang kuliah anak-anak."
Ia mencium Alice, lalu keluar dan menutup pintu.
***
Alice selalu membuat makan malam karena ia selalu pulang lebih dulu semenjak jabatannya diturunkan. John biasanya yang membuat sarapan serta memasak di akhir pekan. Akan tetapi, ketika John pulang malam itu, ia tidak mencium aroma masakan apapun.
Alih-alih, John melihat Alice duduk di sofa, dengan teko itu di pangkuannya. Saat itu sudah lewat pukul sepuluh malam, dan ia sudah menyuruh si karyawan baru pulang dengan alasan ia hanya akan menghalangi pekerjaannya. Akan tetapi, tanpa ada yang membantunya, butuh waktu lebih lama bagi John untuk menyelesaikan semua proses pengiriman. Perut John berkeriuk setelah ia menyadari tak ada makan malam. Ia tak sempat makan apa-apa selain roti panggang saat sarapan. Tukak lambungnya belakangan semakin parah, dan lututnya sakit setelah berdiri seharian di kantor.
Ruang duduk itu gelap, kecuali cahaya dari layar TV yang suaranya dimatikan.
"Alice, kau sedang apa?" Tanya John sambil menyalakan lampu. Alice mencoba menyembunyikan wajahnya di balik bantal sofa, namun John sudah melihat memar di wajahnya.
"Alice, apa yang terjadi?"
Mata kanan Alice nampak bengkak dan berwarna ungu, dan ia nampaknya hanya bisa membuka matanya sedikit. John berlari ke dapur dan mengambil kantung es dari dalam kulkas untuk mengompres matanya. Alice terlonjak ketika kantung es menyentuh matanya, dan menyuruh John untuk melapisinya dengan handuk dulu.
"Alice, apakah ada yang menyerangmu? Haruskah kupanggil polisi?"
John bisa mendengar jantungnya berdegup kencang. Ia cemas istrinya mengalami pendarahan dalam dan akan mati. Di luar itu, ia cemas akan besarnya biaya rumah sakit yang harus dibayar. Mereka sudah berhenti membayar asuransi kesehatan milik Alice.
"Tidak," Alice menggeleng, dan menyodorkan teko kuningan itu ke arah Bill. Di dalamnya, ada tiga lembar uang sepuluh dolar.
"Aku menghantam wajahku dengan setrika," ujar Alice malu-malu. "Teko itu memberiku sepuluh dolar, jadi aku melakukannya dua kali lagi." Ia lalu memberitahu John bahwa teko itu mungkin bisa memberi lebih banyak lagi.
"Ayo, kita ke rumah sakit," ajak John. Tapi Alice menolak.
"Bengkaknya akan hilang."
Setelah mengatur napas dan menenangkan diri dengan menyandarkan kepala di bahu suaminya, Alice mengusulkan agar mereka makan di luar. Pikiran akan makanan enak dan fakta bahwa mereka bisa makan di restoran lagi membuat John sesaat melupakan kekhawatiran akan tingkah aneh istrinya.
"Pikiran kita akan jernih kalau kenyang," ujar John, dengan perut yang semakin berkeriuk.
Saat mereka bersiap hendak pergi, Alice meraih teko kuningan itu. John menyuruhnya meninggalkannya, tapi Alice menolak.
"Bagaimana kalau ada yang masuk dan mencurinya?"
Alice meletakkan teko itu di meja mereka di restoran, diiringi tatapan heran si pelayan yang mendelik ke arah John seolah dirinya pelaku kekerasan rumah tangga. Ini pertama kalinya ada orang yang menuduh John sanggup melakukan hal itu.
"Alice, apa yang terjadi?"
Mata kanan Alice nampak bengkak dan berwarna ungu, dan ia nampaknya hanya bisa membuka matanya sedikit. John berlari ke dapur dan mengambil kantung es dari dalam kulkas untuk mengompres matanya. Alice terlonjak ketika kantung es menyentuh matanya, dan menyuruh John untuk melapisinya dengan handuk dulu.
"Alice, apakah ada yang menyerangmu? Haruskah kupanggil polisi?"
John bisa mendengar jantungnya berdegup kencang. Ia cemas istrinya mengalami pendarahan dalam dan akan mati. Di luar itu, ia cemas akan besarnya biaya rumah sakit yang harus dibayar. Mereka sudah berhenti membayar asuransi kesehatan milik Alice.
"Tidak," Alice menggeleng, dan menyodorkan teko kuningan itu ke arah Bill. Di dalamnya, ada tiga lembar uang sepuluh dolar.
"Aku menghantam wajahku dengan setrika," ujar Alice malu-malu. "Teko itu memberiku sepuluh dolar, jadi aku melakukannya dua kali lagi." Ia lalu memberitahu John bahwa teko itu mungkin bisa memberi lebih banyak lagi.
"Ayo, kita ke rumah sakit," ajak John. Tapi Alice menolak.
"Bengkaknya akan hilang."
Setelah mengatur napas dan menenangkan diri dengan menyandarkan kepala di bahu suaminya, Alice mengusulkan agar mereka makan di luar. Pikiran akan makanan enak dan fakta bahwa mereka bisa makan di restoran lagi membuat John sesaat melupakan kekhawatiran akan tingkah aneh istrinya.
"Pikiran kita akan jernih kalau kenyang," ujar John, dengan perut yang semakin berkeriuk.
Saat mereka bersiap hendak pergi, Alice meraih teko kuningan itu. John menyuruhnya meninggalkannya, tapi Alice menolak.
"Bagaimana kalau ada yang masuk dan mencurinya?"
Alice meletakkan teko itu di meja mereka di restoran, diiringi tatapan heran si pelayan yang mendelik ke arah John seolah dirinya pelaku kekerasan rumah tangga. Ini pertama kalinya ada orang yang menuduh John sanggup melakukan hal itu.
"Apa yang harus kita lakukan dengan itu?" Tanya John setelah menghabiskan saladnya. Restoran Italia itu biasa mereka datangi saat liburan atau ulang tahun, favorit mereka.
"Aku tidak tahu," gumam Alice. Setitik nanah putih merembes keluar dari bengkak di matanya, dan John menghapusnya dengan lap yang dibasahinya dengan air dari gelas.
"Aku cuma tahu kalau inilah kesempatan kita...."
"Kesempatan?"
Si pelayan kembali dengan pesanan mereka. John memesan daging sapi muda di atas sepiring pasta. Alice memesan piring sampel berisi porsi kecil dari tiap menu. Tidak ada yang bicara selama makan. Alice sendiri tak sempat makan siang hari itu. Seharian ia berlari naik turun tangga gedung kantornya, mengantar memo dan surat-surat. Perusahaan tak mengijinkannya mengenakan sepatu keds karena melanggar kode berpakaian, sehingga kakinya sakit dan melepuh. Gajinya kini jauh lebih kecil daripada gajinya dulu saat masih menjadi akuntan. Alice dipecat karena sering membuat kesalahan perhitungan, dan terakhir membuat perusahaan rugi besar karena salah menyusun berkas pengembalian pajak untuk seorang klien penting.
Tagihan makan malam itu sejumlah tiga puluh dolar lebih. Keduanya terkejut, tak menyangka harga-harga makanan telah naik jauh sejak terakhir makan di tempat itu.
"Pakai kartu kredit saja," usul John.
"Tidak bisa, limitnya sudah maksimum," balas Alice.
Mereka berdua terdiam. Uang mereka hanya sembilan belas dolar, belum termasuk tip. Kunjungan ke kampus putri mereka telah menghabiskan banyak uang, belum lagi tambahan uang untuk putri mereka serta biaya untuk bensin mobilnya. Hari gajian pun masih tiga hari lagi.
"Aku akan menulis cek..."
"Restoran ini tidak menerima cek," ujar Alice. John merasa asam lambungnya mulai bertingkah; makanan lezat barusan tak lagi menenangkannya.
Setelah beberapa menit berusaha menghindari bertatapan dengan si pelayan, John akhirnya membawa teko kuningan itu ke kamar mandi pria. Bersyukur bahwa kamar mandi itu dirancang untuk satu orang saja, John mulai menghantamkan tinjunya ke dinding. Mulanya, karena ragu-ragu, ia hanya memeroleh beberapa koin kecil. Kemudian, ia menghantamkan tinjunya lima kali lagi ke dinding yang dilapisi ubun marmer. Ia hanya mendapat kurang dari tiga dolar, namun kepalan tinjunya sudah merah dan berdenyut.
Akhirnya, John menghantamkan tempurung lututnya sekuat tenaga ke tepi wastafel. Rasa sakit yang muncul seolah membekukan seluruh tubuhnya. Terhuyung, ia mengintip ke dalam teko, dan melihat selembar uang lima dolar. Mengerahkan seluruh keberaniannya, John memutar keran air panas, lalu mengulurkan tangannya ke bawah mulut keran selama dua puluh detik, membiarkan kucuran air membakar kulitnya. Dengan mata tertutup rapat, ia mendengarkan suara koin-koin berjatuhan, hingga ia merasa cukup.
Alice merasa malu saat membayar dengan begitu banyak uang receh. Saat mereka berdua meninggalkan restoran, ia tak berani melihat para pengunjung lain. Perlahan, dipapahnya suaminya yang terluka hingga ke mobil, susah payah melihat jalannya hanya dengan satu mata.
Tagihan makan malam itu sejumlah tiga puluh dolar lebih. Keduanya terkejut, tak menyangka harga-harga makanan telah naik jauh sejak terakhir makan di tempat itu.
"Pakai kartu kredit saja," usul John.
"Tidak bisa, limitnya sudah maksimum," balas Alice.
Mereka berdua terdiam. Uang mereka hanya sembilan belas dolar, belum termasuk tip. Kunjungan ke kampus putri mereka telah menghabiskan banyak uang, belum lagi tambahan uang untuk putri mereka serta biaya untuk bensin mobilnya. Hari gajian pun masih tiga hari lagi.
"Aku akan menulis cek..."
"Restoran ini tidak menerima cek," ujar Alice. John merasa asam lambungnya mulai bertingkah; makanan lezat barusan tak lagi menenangkannya.
Setelah beberapa menit berusaha menghindari bertatapan dengan si pelayan, John akhirnya membawa teko kuningan itu ke kamar mandi pria. Bersyukur bahwa kamar mandi itu dirancang untuk satu orang saja, John mulai menghantamkan tinjunya ke dinding. Mulanya, karena ragu-ragu, ia hanya memeroleh beberapa koin kecil. Kemudian, ia menghantamkan tinjunya lima kali lagi ke dinding yang dilapisi ubun marmer. Ia hanya mendapat kurang dari tiga dolar, namun kepalan tinjunya sudah merah dan berdenyut.
Akhirnya, John menghantamkan tempurung lututnya sekuat tenaga ke tepi wastafel. Rasa sakit yang muncul seolah membekukan seluruh tubuhnya. Terhuyung, ia mengintip ke dalam teko, dan melihat selembar uang lima dolar. Mengerahkan seluruh keberaniannya, John memutar keran air panas, lalu mengulurkan tangannya ke bawah mulut keran selama dua puluh detik, membiarkan kucuran air membakar kulitnya. Dengan mata tertutup rapat, ia mendengarkan suara koin-koin berjatuhan, hingga ia merasa cukup.
Alice merasa malu saat membayar dengan begitu banyak uang receh. Saat mereka berdua meninggalkan restoran, ia tak berani melihat para pengunjung lain. Perlahan, dipapahnya suaminya yang terluka hingga ke mobil, susah payah melihat jalannya hanya dengan satu mata.
***
John langsung ambruk di sofa tak lama setelah mereka tiba di rumah. Alice mengurung diri di dapur, dan samar-samar John bisa mendengar "aduh!" dan "sialan!" keluar dari dapur, diikuti dengan suara dentingan uang logam yang membentur bagian dalam teko kuningan.
Esoknya, ia bangun kesiangan. John biasanya selalu mendengar jam weker saat tidur di kamar, namun di ruang tamu, tak ada suara yang membangunkannya. Sudah pukul sepuluh pagi. Alice tak kelihatan, begitu pula dengan tekonya. John langsung bergegas ke kantor, dimana ia kemudian disuruh libur karena ia "kelihatan lelah." Karyawan baru itu bilang ia bisa mengatasinya sendiri, dan ia membuktikannya dengan membereskan urusan pengiriman hanya dalam dua jam. Kecewa, John pulang dengan merana, dan sampai di rumah, melihat bahwa istrinya juga tidak bekerja.
"Kenapa kau pulang?" Tanya Alice. John menatap wajahnya. Dalam cahaya siang, keadaan wajah istrinya nampak jauh lebih buruk daripada malam sebelumya.
"Kenapa kau tidak membangunkanku hari ini?" Balas John.
Alice memberitahunya bahwa ia tidak masuk kerja hari itu. Ia pingsan di garasi ketika sebuah sekop yang digantung di dinding tak sengaja jatuh dan menimpa kepalanya. John meraba kepala Alice hingga jemarinya merasakan benjolan.
"Aku baik-baik saja," ujar Alice.
"Kita harus menghentikan ini!" Teriak John. Ia merampas teko kuningan dari tangan Alice dan menaruhnya ke bagian atas lemari dapur. Tak goyah, Alice menyeret kursi dan memanjat, mengambil kembali teko itu.
"Kita punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya!" Balas Alice, memegangi teko itu lebih erat. Kali ini, ia tak mau membiarkan John merampasnya.
"Memperbaiki semuanya?" John dengan lembut menjelaskan bahwa satu-satunya jalan adalah kembali bekerja lembur. "Hari ini kita sudah rugi...."
"Kerja lembur tak akan pernah cukup, John. Setiap kali kita mendapat uang lebih, selalu saja ada yang rusak atau anak-anak butuh uang...."
Mereka bertengkar selama sejam, dan Alice terus mencengkeram teko itu. Ia memanggil John pecundang hingga tiga kali, dan John yang emosi menyebutnya ibu yang buruk. Belum pernah mereka memperlakukan satu sama lain seperti itu sebelumnya. Ketika pertengkaran itu akhirnya usai, keduanya membungkuk kelelahan dan kelaparan karena belum sarapan pagi. Alice membuka tutup teko kuningan, dan menemukan berlembar-lembar uang dua puluh dolar. Jumlahnya pasti lebih dari empat ratus dolar.
"Tapi...bagaimana bisa?" Tanya John.
Sebagai jawaban, Alice meludahi wajahnya. Lantas, ia memberitahu John bahwa ia selalu mengusahakan untuk makan siang di rumah, berharap tukang pos akan datang dan menyapanya. Selembar uang dua puluh dolar muncul di dalam teko.
"Sekarang, kau lakukan yang sama padaku," tukas Alice.
"Kau perempuan jalang!" Seru John. Suara dentingan uang logam menyusul.
"Tidak, kau harus sungguh-sungguh. Beritahu aku apa yang kau paling benci dariku, atau hal terburuk apa yang pernah kau lakukan. Sesuatu yang akan sangat menyakiti perasaanku."
John terduduk di kursi makan, berusaha memikirkan sesuatu sambil membayangkan wajah tukang pos langganan mereka.
"Aku pernah tidur dengan Ellen Waterson...."
"Aku sudah tahu itu," potong Alice.
"Tidak, aku tidur dengannya setelah kita mulai kencan," ujar John dengan nada penuh kebencian.
Itu adalah rahasianya. Kata-kata itu telah menggumpal di bawah kulitnya selama dua puluh tahun. Ia bahkan bisa mengendusnya saat tidur dengan Alice setiap malam. Kata-kata yang telah berlumut, berkerak di bawah kulitnya.
Wajah Alice memucat, namun ia kembali tersenyum ketika membungkuk dan melihat selembar uang lima puluh dolar di dalam teko.
"Teruskan."
Keduanya pun mula membongkar rahasia masing-masing. Hal-hal yang suami istri tak akan pernah katakan di bawah satu atap. John memberitahu Alice tentang karyawan wanita baru di kantornya, yang baru lulus kuliah dan akan menggantikan pekerjaannya, dan betapa tegak dan penuhnya payudaranya. Alice bercerita tentang pria-pria yang pernah bersamanya, dan bagaimana ia mengijinkan mereka melakukan hal-hal yang Alice tak pernah ijinkan John melakukannya. Di akhir hari, mereka berhasil mengumpulkan seribu dolar lebih. Jauh lebih banyak dari penghasilan mereka dalam seminggu.
Mereka meneruskan hal itu hingga esok harinya, saling berteriak penuh kemarahan hingga masing-masing menyingkir ke sudut ruangan dan menangis sampai tertidur. Pada hari keempat, John mendapat telepon dari atasannya, yang memintanya untuk tidak usah repot-repot datang lagi, karena karyawan baru itu sudah menggantikannya.
"Baiklah," jawab John. "Saya toh sudah menemukan pekerjaan baru." Atasan John agak terkejut dengan tanggapan tanpa emosi ini.
Alice sendiri sudah keluar dari pekerjaannya. Akan tetapi, mereka sudah kehabisan pengakuan dan bahan hinaan (hinaan yang tidak sungguh-sungguh rupanya tak menghasilkan apa-apa), dan mereka masih harus mengusahakan sesuatu sekedar untuk mencukupi belanja sehari-hari. Setiap hari, mereka tidur sampai menjelang siang, kemudian duduk di meja dapur sambil membungkuk di atas teko kuningan itu.
"Aku selalu menganggapmu murahan saat kita masih di sekolah menengah," ujar John.
Cring. Cring. Cring.
"Kau tak pernah membuatku orgasme," balas Alice.
Tiga lembar uang dua puluh dolar muncul.
Alice kini sudah belajar mengenali keampuhan hinaannya dengan melihat ekspresi terluka suaminya. Ejekan, penyiksaan diri, kata-kata hinaan yang telah terlontar, semuanya membawa dampak yang lebih dalam bagi John. Ekspresi wajahnya kini tak lagi kembali normal.
***
Memasuki bulan ketiga, teko itu semakin sedikit memberi uang setiap harinya. Alice mulai rutin menghantam jari-jemarinya dengan pintu lemari setiap hari sekedar untuk mendapat jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Keduanya menghitung-hitung bahwa mereka setidaknya harus mendapat sekitar seratus dolar per hari.
Ketika putri sulung mereka menelepon dan memberitahu rencana kunjungannya di akhir pekan, Alice dengan lembut menyarankan agar ia tidak usah datang. Putrinya tak mendengarkan. Ia tanpa terduga muncul di pintu depan rumah mereka esok malamnya.
Ketika sang anak memasuki rumahnya, ia melihat keadaannya sangat berbeda dari pertama kali ia meninggalkannya. Foto-foto dalam bingkai di dekat gantungan mantel kini berantakan di lantai, kaca mereka pecah. Beberapa oleh kepalan tinju, yang lain dilempar karena emosi. Rambut ibunya dipotong sangat pendek, nyaris cepak. Alice memberitahu putrinya bahwa ia sedang mencoba gaya rambut baru, walau sebenarnya ia telah menarik lepas rambutnya untuk mendapat uang, sedemikian rupa sehingga Alice harus mencukur kepalanya agar rambutnya tumbuh rata.
Penampilan sang ayah jauh lebih mengejutkan. Rambut kelabu John semakin banyak, dan ia nampak semakin gemuk. Keduanya selalu makan dan tak lagi berolahraga. Mereka juga tak pernah meninggalkan teko kuningan itu, takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sedikit uang.
Ketika sang anak duduk di sofa sambil menyesap teh, merenungkan keadaan rumahnya yang berubah, ia mulai mengoceh soal kampus dan para dosennya. Biasanya, Alice dan John akan mendengarkan dengan telaten, berkomentar, serta mengajukan pertanyaan. Kali ini, tak ada seorangpun yang bicara. Pikiran keduanya dipenuhi soal teko kuningan itu, yang diletakkan di meja kopi di depan mereka.
Sang anak mengangkat teko itu, dan kedua orangtuanya langsung menerjang serta menyambarnya.
"Itu barang antik," ujar Alice, meletakkan kembali teko itu di atas meja.
"Kenapa matamu, ibu?" Tanya si anak kemudian. Ada empat luka terpisah di atas mata ibunya yang baru bisa kelihatan dari dekat, namun luka bekas dihantam setrika nampak paling menonjol mengerikan.
"Tak apa-apa, aku jatuh," gumam Alice. Ia menatap tamak ke arah kulit putrinya yang mulus, bebas memar, luka dan bekas cubitan. Ketika ia memeluknya sebelum naik ke lantai dua untuk tidur, Alice menghadiahinya dua cubitan keras di lengan dan punggungnya.
"Aduh! Kenapa ibu melakukan itu!?" Seru si anak perempuan, tak mendengar bunyi dentingan uang logam di dalam teko.
"Maaf," gumam Alice, kecewa mendengar suara uang logam yang familiar.
Ketika Alice mengulurkan koper putrinya, ia dengan sengaja menghantamkannya ke tulang keringnya. Putrinya menjerit dan melolong kesakitan, melompat-lompat sementara Alice berkali-kali meminta maaf, telinganya mendengar suara kucuran uang logam.
John dan Alice menunggu putri mereka keluar bersama teman-teman sekolah menengahnya dan kemudian setelah ia tidur, sebelum memulai ritual ejekan dan siksaan fisik mereka. Ketika pada suatu pagi putri mereka bertanya mengapa bibir ibunya membengkak, keduanya tak menjawab.
Sang anak akhirnya pulang pada hari Minggu pagi, lebih cepat daripada yang direncanakannya, karena ibunya 'tanpa sengaja' tersandung dan membuatnya terdorong jatuh dari tangga ketika berjalan di belakangnya. Sikunya kemungkinan retak, dan ia ingin kembali secepatnya agar bisa menggunakan layanan kesehatan untuk mahasiswa. Pikirnya, aneh sekali orangtuanya tidak memberinya uang bensin.
"Kau harusnya tak melakukannya," gumam John saat mereka berdiri di depan rumah dan melambaikan tangan ke arah putri mereka.
"Itu lima puluh dolar tambahan yang bisa kita gunakan untuk uang kuliahnya!" Desis Alice.
Setelah mereka kehabisan rahasia memalukan untuk dibongkar, dan dengan kondisi rumah kacau balau, keduanya pun terpaksa kembali menyakiti tubuh mereka. John menelepon mantan atasannya dan meninggalkan pesan untuk memohon pekerjaannya kembali, namun mantan atasannya tak pernah membalasnya. Tagihan uang kuliah putri mereka datang tiap tiga bulan, belum lagi bayaran hipotek rumah, tagihan listrik dan air, serta tagihan kartu kredit. John pun harus membawa Alice ke rumah sakit karena benturan keras di kepala yang dilakukannya sendiri dengan sekop di gudang.
Seorang petugas polisi mampir ke rumah mereka dan menanyai John. Ia menuliskan jawaban-jawaban John di buku catatannya, serta menunjukkan foto-foto cedera Alice.
"Dia jatuh?" Tanya si polisi.
John mengangguk tanpa menatap wajah si polisi.
Setiap menjelang akhir pekan, John pergi ke bank membawa seember uang logam, dan menukarnya dengan uang kertas. Akan tetapi, teko itu bahkan semakin sedikit mengeluarkan uang logam. Mereka mengharap akan bisa mendapat empat ratus dolar setiap minggu, namun jumlah itu kini berkurang menjadi dua ratus lima puluh dolar.
"Kulkasnya rusak," lapor Alice suatu ketika, ketika John pulang dari bank.
"Apa? Kenapa bisa?"
"Entahlah. Mungkin karena kau selalu meninjunya."
Pribadi Alice perlahan berubah setiap harinya. John curiga ia membuat dirinya sendiri kembali nyaris gegar otak ketika ia 'terpeleset' di kamar mandi, membuat John harus mengangkat tubuhnya keluar, basah kuyup dengan kepala berdarah. Alice bilang itu kecelakaan, tetapi teko kuningan itu ada di dekatnya. Mereka telah menemukan bahwa tekonya hanya bekerja ketika orang yang terluka ada di dekatnya.
"Jadi, kau menyalahkanku karena kulkasnya rusak?" Tanya John. "Lalu, bagaimana dengan mobil? Aku bisa menyalahkanmu karena kaca depan yang pecah itu."
Kulit Alice kini pucat kebiruan. Matanya tak lagi menyisakan warna putih, hanya hijau dan merah. Kurang tidur membuatnya mendapat sedikit uang, tapi bukan itu sebabnya ia terjaga nyaris setiap malam. Ia kesakitan. Kepalanya berdenyut-denyut, namun Alice menolak pergi ke dokter karena mereka harus mengeluarkan uang lagi.
Ketika tukang reparasi akhirnya datang, ia memberitahu mereka bahwa garansi kulkas tersebut tidak menutupi perbaikan kerusakan yang satu ini. Alice langsung meledak di depannya. Tukang reparasi itu pendek, gemuk dan botak, mengenakan cincin kawin emas dan perak, serta baju terusan biru dengan label nama bertuliskan 'Randy.'
"Nyonya, bukan aku yang membuat aturan...."
John, yang sedang menyeka luka di dagunya, berjalan masuk ke dapur dan melihat istrinya sedang menghantamkan sendok kayu ke kepala si tukang reparasi. Ia tak bisa menghindar karena lebih tua, gemuk, dan rupanya sedikit pincang.
"Alice!" Teriak John, berusaha menarik istrinya. Suara dentingan sendok yang menghantam cincin si tukang reparasi saat ia menutupi wajahnya berirama dengan suara kucuran uang logam di dalam teko. Ketika John merangkul tubuhnya dari belakang, Alice mengangkat kakinya dan menendang wajah si tukang reparasi, mematahkan hidungnya, darahnya mengucur hingga menetes ke lantai.
"Kau gila!" Jerit si tukang reparasi. "Istrimu perempuan jalang gila!"
"Dia tidak gila," ujar John tenang. Ia berjalan ke arah teko kuningan dan membuka tutupnya, mengeluarkan selembar uang seratus dolar yang baru muncul. Diulurkannya uang itu ke arah si tukang reparasi. "Apakah ini cukup?"
Pria itu tertawa. "Aku akan menuntut. Dia mematahkan hidungku!"
John melirik Alice. Kulit istrinya yang membiru nampak berpendar di bawah cahaya matahari yang menerobos masuk. Telepon berdering di kejauhan, namun tak ada yang mendengarnya. Satu-satunya yang bisa mereka dengar hanyalah suara koyakan basah ketika Alice menancapkan pisau dapur ke perut si tukang reparasi.
Pria itu berusaha mencabut pisau dari perutnya, namun Alice mendorongnya lebih dalam dan memutarnya, seperti yang sering dilihatnya di film-film.
"Apa yang kau lakukan!?" Teriak John. Pikirannya seketika berpacu, berusaha menemukan cara menyembunyikan mayatnya. Bagaimana ia bisa melindungi istrinya?
Tubuh pria itu perlahan jatuh ke lantai dapur. Ia masih berusaha berdiri, namun kakinya menekuk pasrah di bawahnya. Ketika ia terjatuh, Alice menendangnya sekali sebelum jantungnya berhenti berdetak.
"Apa yang sudah kau lakukan?" John bertanya lagi.
Alice membungkuk di atas tubuh pria itu, menusuknya tiga atau empat kali lagi, berharap pria itu masih merasakan sakit. Di bawah tatapan ngeri John, Alice berdiri dan dengan tenang melangkah ke arah teko kuningan. Ia mengangkat tutupnya. Wajahnya yang ternoda percikan darah menampakkan senyuman.
"Lihat!" Serunya, menunjukkan isi teko kepada John, yang menolak melihatnya. Berlembar-lembar uang seratus dolar ada di dalamnya.
"Kau membunuh orang!" Teriak John, melirik ke arah jendela dapur. Tak ada seorangpn terlihat. "Kita harus memasukkan mayatnya ke truknya di luar. Coba cari di mana ia menaruh kuncinya."
John menyambar handuk untuk mengelap darah di lantai dapur. Ketika ia kembali, istrinya membungkuk lagi di atas mayat tersebut sambil menggenggam pisau.
"Tidak bisa kalau orangnya sudah mati," gumam Alice.
"Bisakah kau bantu aku?" Tukas John, mengeluarkan beberapa botol cairan pembersih. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum ada yang tahu dia hilang."
Alice tidak mendengarkan, hanya menatap ke dalam teko yang sudah dikosongkannya.
"Kita bisa hidup enak," gumamnya. "Ada sekitar lima belas orang tetangga di sekitar rumah yang percaya pada kita. Don di seberang jalan punya pistol di lemarinya, dia selalu mengisinya...." Alice sudah melihatnya saat Don menunjukkannya di perayaan 4 Juli.
"Ini sepuluh ribu dolar," gumam Alice, tangannya menyapu tumpukan uang kertas seratus dolar di lantai. "Kita bisa hidup seperti di surga...."
Tamat